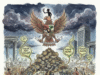Malam menyelimuti Nagari Sago dengan langit gelap bertabur bintang. Angin dingin berdesir pelan, membawa aroma daun pisang yang dibakar untuk masak di dapur-dapur rumah gadang. Di balai adat, sebuah bangunan kayu dengan atap gonjong yang sedikit miring karena usia, lampu minyak menyala terang, menerangi wajah-wajah warga yang penuh cemas. Hari ini bukan hari biasa—rapat besar yang dijanjikan ninik mamak akhirnya tiba, dan hampir seluruh nagari berkumpul.
Alam berdiri di sudut balai, bersandar ke tiang kayu dengan ladiang terselip di pinggang. Baju destarnya yang hitam masih kotor bekas lumpur, celana galembongnya sedikit berderit saat dia bergeser. Dia tak suka keramaian macam ini—terlalu banyak omong, terlalu sedikit tindakan, pikirnya. Tapi dia datang, seperti yang dia janjikan pada Pak Tuo Sani kemarin. Hasan berdiri di sampingnya, matanya jelalatan lihat orang-orang yang terus berdatangan.
Di tengah balai, para ninik mamak duduk melingkar. Pak Tuo Sani, dengan deta hitamnya yang sudah usang, duduk di posisi paling depan. Pak Cik Amin di sampingnya, janggut putihnya bergoyang pelan saat dia mengunyah sirih. Bundo Sari ada di sebelah kiri, tangannya memegang tongkat kayu tua, matanya tajam menatap kerumunan. Engku Jamal juga hadir, wajahnya serius sambil memegang selembar kain yang dia gunakan untuk lap keringat.
“Assalamualaikum, warga Nagari Sago,” sapa Pak Tuo Sani, suaranya berat tapi jelas, memecah bisik-bisik di ruangan. “Kita kumpul malam ini karano ada kabar yang tak bisa kita abaikan. Engku Jamal bawa cerita dari Bukiktinggi, dan kita harus putuskan langkah.”
“Waalaikumsalam,” jawab warga serentak, meski nada suara mereka bercampur gelisah.
Engku Jamal berdiri, tangannya menggenggam erat kain itu. “Iyo, Pak Tuo. Di pasar Bukiktinggi, orang-orang bilang Belanda mau naikkan pajak. Bukan cuma beras, tapi tanah kita juga. Mereka bilang, kalau kita tak bayar, sawah kita diambil. Aku dengar sendiri dari pedagang, sampe utusan Belanda yang bawa kertas perintah.”
Riuh rendah langsung terdengar. Ada yang mengeluh pelan, ada yang mengumpat keras. “Apa lagi yang mereka mau? Kita sudah susah makan!” teriak seorang laki-laki dari belakang. Alam mengenali suara itu—Sutan Mudo, petani yang sawahnya kecil tapi mulutnya besar.
“Tenang dulu,” kata Pak Cik Amin, mengangkat tangan. “Kita tak bisa gegabah. Belanda punya tentara, senjata api. Kalau kita lawan langsung, apa yang kita punya? Ladiang sama cangkul?”
Alam tak tahan lagi diam. Dia melangkah maju, suaranya lantang memotong. “Pak Cik, iyo, mereka punya senjata. Tapi kita punya hati, punya akal, punya nagari yang harus kita jaga! Kalau kita cuma diam, apa bedanya kita sama ayam di kandang, tunggu dipotong?”
Beberapa warga mengangguk, ada yang berbisik setuju. Tapi Pak Cik Amin cuma geleng kepala. “Kau ini, Alam. Mulut kau tajam, tapi pikir dulu. Kita tak bisa lawan Belanda dengan semangat doang.”
“Kalau tak lawan, kita mati pelan-pelan, Pak Cik,” balas Alam, matanya menyala. “Kau bilang kita cuma petani, tapi nenek moyang kita pernah buat Belanda takut. Silat kita, adat kita—itulah senjata kita.”
Bundo Sari tertawa kecil, suaranya serak menggema di balai. “Nak ini punya nyali, Pak Cik. Tapi dia tak salah. Kita tak bisa cuma pasrah. Tapi iyo juga, kita tak bisa lawan langsung. Harus ada akal.”
Pak Tuo Sani mengangguk pelan, tangannya mengelus deta di kepalanya. “Bundo Sari bae. Kita harus cari jalan tengah. Engku Jamal, kau bilang apa yang kau dengar di pasar—ada cara lain tak yang nagari lain pakai?”
Engku Jamal menghela napas, wajahnya penuh kerut. “Ada nagari yang coba bayar pajak dengan barter—beras, kopi, kayu. Tapi Belanda tak selalu mau. Mereka nak duit, Pak Tuo. Duit yang kita tak punya banyak.”
“Kalau duit yang mereka mau, kita cari duit!” potong Alam lagi, melangkah lebih dekat ke lingkaran ninik mamak. “Kita dagang, kita jual apa yang kita punya. Bukiktinggi kan dekat, pasar ramai. Kita bawa beras, kayu manis, apa saja—daripada kita serahkan sawah!”
Warga mulai ramai berbisik lagi. Ada yang setuju, ada yang ragu. “Dagang? Kau pikir gampang, Alam? Jalan ke Bukiktinggi jauh, bandit banyak,” sahut Sutan Mudo, nada suaranya penuh sindir.
“Bandit takut sama ladiang aku, Sutan,” jawab Alam cepat, tangannya menepuk gagang ladiang di pinggang. Beberapa pemuda di belakang tertawa, tapi Sutan Mudo cuma mendengus.
“Alam, kau punya semangat, tapi ini tak semudah kau bilang,” kata Pak Tuo Sani, suaranya tetap tenang. “Dagang butuh orang, butuh rencana. Dan Belanda tak sabar tunggu kita.”
“Pak Tuo, kalau kita tak coba, kita tak tahu,” balas Alam, tak mundur. “Biar aku yang pimpin. Aku ambil beberapa nak lain, kita ke Bukiktinggi, cari duit. Kalau berhasil, kita bayar pajak. Kalau gagal, setidaknya kita tak cuma duduk diam.”
Bundo Sari menatap Alam lama, matanya penuh tanya tapi ada senyum tipis di bibirnya. “Kau ini parewa beneran, Alam. keras, tapi ada akal. Aku setuju coba, tapi kau harus janji—jangan gegabah di jalan.”
Alam nyengir, pertama kali malam itu. “Janji, Amai. Aku bawa ladiang, bukan cuma buat gaya.”
Pak Tuo Sani menghela napas panjang, lalu pandang warga yang masih riuh. “Baiklah. Kita kasih Alam kesempatan. Besok kau kumpulkan nak-nak yang mau ikut, kita rencanakan. Tapi ini cuma langkah awal. Kita tetap harus pikir cara lain.”
Warga mulai berpencar setelah rapat selesai, tapi Alam tak langsung pulang. Dia berdiri di depan balai, pandang ke langit gelap. Hasan mendekat, suaranya pelan. “Kau yakin, Alam? Ini tak main-main.”
Alam menoleh, matanya penuh tekad. “Iyo, Hasan. Aku tak main-main. Nagari ini satu-satunya yang aku punya. Kalau aku tak jaga, siapa lagi?”
Hasan cuma diam, tapi dia tahu—Alam tak akan mundur. Malam itu, balai adat jadi saksi awal perjuangan Nagari Sago. Di hati Alam, ada api yang makin membesar—api yang bilang dia harus buktikan kata-katanya, apa pun risikonya.