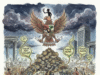Pagi di Nagari Sago dimulai sebelum matahari terbit, saat suara azan Subuh berkumandang dari surau kecil di pinggir kampung. Alam bangun dari tikar di gubuknya, masih mengantuk tapi buru-buru ambil air wudu dari tempayan. Dia pakai baju destar hitam yang agak kusut, celana galembongnya sedikit berderit saat melangkah ke surau. Di sana, dia ketemu Hasan, Bujang, dan Arip—mereka sholat Subuh berjamaah, dipimpin Sutan Daud yang suaranya serak tapi penuh khusyuk. Selesai sholat, Alam duduk sejenak di serambi surau, pikirannya sudah ke rencana hari ini, tapi dia diam, hormati doa yang masih dibaca anak bujang lain.
Kabut tipis masih menyelimuti sawah saat matahari mulai menyelinap, membakar udara dengan panas yang perlahan naik. Bunyi ayam berkokok bercampur dengan suara langkah warga yang mulai beraktivitas—ada yang ke sawah, ada yang bawa kayu bakar. Di dekat gubuk Alam, beberapa anak bujang berkumpul, wajah mereka penuh tanya dan semangat yang bercampur ragu.
Alam berdiri di depan mereka, ladiang terselip di pinggang, baju destarnya sedikit berkerut dari tidur semalam. Matanya tajam, penuh tekad. Di depannya ada Hasan, anak bujang kurus tapi lincah seperti kucing; lalu ada Bujang, anak bujang besar yang kuat tapi pendiam; dan Arip, yang mulutnya cerewet tapi tangannya cekatan. Mereka adalah anak bujang yang Alam ajak malam tadi setelah rapat di balai adat.
“Jadi, Alam, kau serius nak bawa kita ke Bukiktinggi?” tanya Arip, tangannya memegang sebatang kayu kecil yang dia mainkan. Nada suaranya setengah bercanda, tapi matanya serius.
“Iyo, Arip. Kita tak ada pilihan lain. Belanda nak duit, dan duit tak datang sendiri kalau kita cuma duduk di sini,” jawab Alam, suaranya tegas. Dia melangkah ke tengah, tangannya menunjuk ke arah sawah di kejauhan. “Itu tanah kita. Kalau kita tak cari jalan, mereka ambil semua.”
Hasan mengangguk pelan, meski wajahnya masih penuh gelisah. “Tapi, Alam, jalan ke Bukiktinggi tak gampang. Hutan lebat, bandit ada, dan kita tak tahu pasar bakal nerima barang kita apa tak.”
“Bandit takut sama ini,” kata Alam, menepuk ladiang di pinggangnya dengan senyum kecil. “Dan pasar? Kita bawa apa yang mereka butuh—beras, kayu manis, kopi. Nagari kita punya banyak, cuma kita tak pernah coba jual bener-bener.”
Bujang, yang biasanya cuma diam, akhirnya buka suara, nadanya pelan tapi dalam. “Aku ikut, Alam. Tapi kita butuh lebih banyak anak bujang. Kita tak bisa cuma berempat.”
Alam nyengir, senang dengar Bujang setuju. “Iyo, Bujang. Makanya aku nak kau sama Hasan cari anak bujang lain yang mau ikut. Pilih yang kuat, yang tak takut kerja keras. Aku sama Arip urus barang yang bakal kita bawa.”
Arip mendengus, tapi tak protes. “Kau suruh aku angkat-angkat barang, Alam? Aku lebih pinter ngomong daripada angkut beras.”
“Kau pinter ngomong, makanya nanti kau yang nawar di pasar,” balas Alam cepat, membuat Hasan dan Bujang tertawa kecil. Arip cuma geleng kepala, tapi ada senyum di sudut bibirnya.
Mereka duduk melingkar di depan gubuk, Alam ambil sebatang kayu dan gambar garis-garis kasar di tanah. “Ini rencana aku. Kita kumpulkan barang tiga hari dari sekarang—beras yang lebih dari panen kemarin, kayu manis dari bukit, sama kopi kalau ada yang punya stok. Kita bawa pake kerbau, lambat tapi aman. Jalan ke Bukiktinggi ambil yang biasa dilewati pedagang, lambat-lambat sampe tiga hari.”
“Kerbau? Kau yakin tak ada yang lebih cepat?” tanya Hasan, alisnya terangkat.
“Kerbau kita punya, Hasan. Kuda mahal, dan kita tak punya duit buat sewa. Lagipula, kerbau kuat bawa banyak,” jawab Alam, tangannya terus menggambar di tanah. “Kita bagi tugas. Bujang sama anak bujang lain yang kuat jaga barang di belakang. Aku sama Hasan di depan, awasi jalan. Arip urus barang sama nawar nanti di pasar.”
Arip mengangguk, mulai serius. “Baiklah. Tapi kalau bandit datang, kau yang lawan duluan, Alam. Aku tak nak ladiangku patah.”
Alam tertawa lepas. “Janji, Arip. Tapi kau bantu kalau aku kewalahan, ya?”
Saat matahari naik tinggi, azan Zuhur terdengar dari masjid kecil di tengah nagari. Alam dan anak bujang berhenti, cari tempat di dekat gubuk. Mereka ambil air dari tempayan, wudu, lalu sholat berjamaah di atas tanah dengan tikar tua yang Alam keluarkan dari gubuk. Selesai sholat, Arip usul bajamba—makan bersama dalam talam besar—buat ngobrol sambil isi perut. Mereka ambil lemang kecil sama rendang sisa pagi tadi, duduk melingkar di tikar, makan dari talam kayu tua sambil lanjut rencana. Alam ambil suap besar, sambil bilang, “Makan macam ini bikin kita kuat, biar rencana kita lancar.”
Tiba-tiba suara langkah mendekat. Alam menoleh, lihat Aisyah datang dengan langkah cepat, tangannya memegang keranjang kecil berisi daun pisang. Rambutnya disanggul rapi, bajunya sederhana tapi bersih—khas anak gadih Minang yang tak suka berlebihan. Matanya menatap Alam dengan campuran khawatir dan penasaran.
“Alam, kau beneran nak ke Bukiktinggi?” tanya Aisyah langsung, tak buang waktu.
“Iyo, Yah. Kau dengar dari mana?” balas Alam, berdiri dan membersihkan tangan dari sisa rendang.
“Dari ibu. Katanya kau bilang di rapat tadi malam. Kau tahu itu bahaya, kan?” suara Aisyah pelan, tapi ada nada tegas di dalamnya.
Alam nyengir, tapi matanya lembut lihat Aisyah. “Iyo, aku tahu. Tapi kalau kita tak coba, nagari ini habis, Yah. Belanda tak tunggu kita siap.”
Aisyah diam sejenak, lalu taruh keranjang di tanah. “Ini dari ibu—makan buat kau sama anak bujang ini. Kalau kau pergi, jangan lupo makan. Aku tak nak dengar kau pingsan di jalan.”
Hasan dan Arip langsung mendekat, lihat isi keranjang—rendang sama lemang kecil. “Wah, Aisyah, kau bawa surga ke sini!” canda Arip, tapi cepat-cepat mundur pas Aisyah melotot.
“Terima kasih, Yah,” kata Alam, suaranya tulus. “Kau tak usah khawatir. Aku balik bawa duit, bukan luka.”
Aisyah cuma mengangguk, tapi matanya tak bisa bohong—dia khawatir. Dia berbalik pergi, langkahnya pelan meninggalkan gubuk. Alam pandang punggungnya sampe hilang, lalu balik ke anak bujang yang masih lihat dia.
“Apa yang kau pandang? Kerja!” bentak Alam, tapi ada senyum di wajahnya. Mereka tertawa, lalu bergerak. Hasan sama Bujang pergi cari anak bujang lain, sementara Arip ikut Alam ke gudang kecil di pinggir nagari, lihat stok beras yang masih ada.
Sore itu, Alam berdiri di depan gudang, hitung karung beras yang bisa mereka bawa. Pikirannya penuh—jalan panjang, bandit, pasar yang tak pasti. Tapi di hatinya, dia tahu ini harus dilakukannya. Dia ingat kata Bundo Sari tadi malam—jangan gegabah. Tapi Alam juga tahu, kadang gegabah adalah satu-satunya cara buat hidup.
“Alam, ini cukup tak?” tanya Arip, nunjuk karung-karung yang sudah ditumpuk.
“Cukup buat awal, Arip. Kalau ini laku, kita balik bawa lebih banyak,” jawab Alam, tangannya menyeka keringat di dahi.
Matahari mulai condong ke barat, membawa bayangan panjang di Nagari Sago. Alam pandang ke arah bukit, tempat kayu manis tumbuh liar. Dia tahu perjalanan ini tak cuma soal duit—ini soal bukti, buat ninik mamak, buat warga, dan buat dirinya sendiri. Dia pegang ladiang di pinggang, rasakan bobotnya yang dingin. “Kita mulai besok,” gumamnya pelan, tapi tekadnya sekeras batu. Malam nanti, dia tahu, mereka akan ke surau lagi untuk sholat Maghrib, minta perlindungan buat langkah besar yang akan datang.